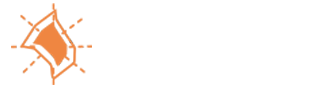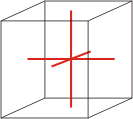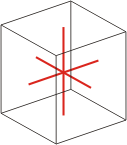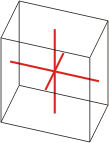Mineral adalah senyawa alami yang terbentuk melalui proses geologis. Istilah mineral tidak hanya sebatas pada bahan komposisi kimia, tetapi juga mencakup struktur kristal dari mineral itu sendiri. Mineral meliputi unsur murni dan senyawa seperti garam, mulai dari struktur yang sederhana hingga silikat kompleks dengan ribuan bentuk yang diketahui. Senyawaan organik biasanya tidak termasuk dalam kategori mineral.
A. Definisi dan Klasifikasi Mineral
Ilmu yang mempelajari mineral disebut mineralogi. Agar suatu senyawa dapat diklasifikasikan sebagai mineral sejati, ia harus berupa padatan dengan struktur kristal tertentu. Menurut definisi International Mineralogical Association (IMA) pada tahun 1995, mineral adalah unsur atau senyawa yang memiliki struktur kristal dan terbentuk melalui proses geologi alami.
B. Identifikasi Mineral
Mineral dapat diidentifikasi berdasarkan sifat fisiknya yang mencakup:
- Kilap: Tampilan permukaan mineral saat terkena cahaya.
- Warna: Warna yang tampak pada mineral.
- Kekerasan: Diukur menggunakan skala Mohs.
- Cerat: Warna serbuk mineral saat digoreskan pada plat porselen.
- Belahan: Kemampuan mineral membelah sepanjang bidang tertentu.
- Pecahan: Cara mineral patah tanpa arah tertentu.
- Bentuk (form): Pola geometris yang membentuk kristal mineral.
Sistem Kristal Mineral (Kristalografi Sistem Kristal)
Kristal adalah padatan dengan atom, molekul, atau ion yang tersusun dalam pola tiga dimensi berulang. Berdasarkan unsur simetrinya, kristal dibagi menjadi tujuh sistem utama, yaitu:
- Isometrik
- Tetragonal
- Hexagonal
- Trigonal
- Orthorhombik
- Monoklin
- Triklin
Sistem-sistem ini diklasifikasikan berdasarkan elemen simetri seperti bidang, sumbu, dan pusat simetri. Berikut penjelasan detailnya:
1. Sistem Isometrik (Kubus)
Sistem ini memiliki tiga sumbu kristal yang saling tegak lurus dengan panjang sama (a = b = c) dan sudut 90°. Contohnya:
- Mineral: Emas (gold), pirit (pyrite), galena, halite, fluorite.
- Kegunaan: Emas digunakan dalam perhiasan, galena sebagai sumber utama timbal.
2. Sistem Tetragonal
Sistem ini memiliki tiga sumbu tegak lurus, di mana dua sumbu memiliki panjang yang sama (a = b ≠ c) dengan sudut 90°.
- Mineral: Rutil, autunit, pirodusit, scapolit.
- Kegunaan: Rutil sebagai sumber titanium, pirodusit dalam industri logam.
3. Sistem Hexagonal
Memiliki empat sumbu kristal; tiga sumbu horizontal saling membentuk sudut 120° (a = b = d ≠ c) dan satu sumbu tegak lurus.
- Mineral: Kuarsa (quartz), korundum (corundum), hematit (hematite), kalsit (calcite).
- Kegunaan: Kuarsa digunakan dalam elektronik, hematit sebagai bijih besi.
4. Sistem Trigonal
Sering dianggap bagian dari sistem hexagonal. Perbedaannya terletak pada pola dasar segitiga.
- Mineral: Turmalin (tourmaline), sinabar (cinnabar).
- Kegunaan: Sinabar sebagai sumber utama merkuri.
5. Sistem Orthorhombik
Memiliki tiga sumbu kristal yang saling tegak lurus tetapi dengan panjang berbeda (a ≠ b ≠ c).
- Mineral: Stibnit (stibnite), kalsit, aragonit.
- Kegunaan: Aragonit digunakan dalam pengobatan dan bahan baku semen.
6. Sistem Monoklin
Memiliki tiga sumbu kristal, satu sumbu miring (a ≠ b ≠ c, sudut γ ≠ 90°).
- Mineral: Azurit, malakit, gypsum, epidot.
- Kegunaan: Malakit sebagai batu permata, gypsum untuk bahan konstruksi
7. Sistem Triklin
Memiliki tiga sumbu yang tidak saling tegak lurus (a ≠ b ≠ c, sudut α, β, γ ≠ 90°).
- Mineral: Albite, kaolinite, mikroklin.
- Kegunaan: Kaolinite sebagai bahan keramik, mikroklin untuk dekorasi.
Sistem Kristal Mineral
Kristal adalah suatu padatan yang atom, molekul, atau ion penyusunnya terkemas secara teratur dan polanya berulang melebar secara tiga dimensi. Kristal memiliki unsur-unsur untuk identifikasi, yang disebut dengan unsur-unsur simetri kristal
Kristal dapat diklasifikasikan menjadi tujuh kelompok besar, yang
disebut system kristal. Ke-7 kelompok sistem kristal itu, yaitu sistem
isometrik, sistem hexagonal, sistem trigonal, sistem tetragonal, sistem
orthorombik, sistem monoklin, dan sistem triklin
Dari beberapa sistem kristal dapat dibagi lebih lanjut menjadi kelas-kelas kristal yang jumlahnya 32 klas. Tetapi untuk sementara kita hanya mempelajari 7 sistem kristal yang utama. Penentuan klasifikasi kristal tergantung dari banyaknya unsur-unsur simetri yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur simetri tersebut meliputi, bidang simetri, sumbu simetri, dan pusat simetri
1. Bidang Simetri
Bidang simetri pada kristal adalah bidang yang dapat membelah kristal menjadi 2 bagian yang sama, dimana bagian yang satu merupakan bayangan dari yang lain. Bidang simetri ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bidang simetri aksial dan bidang simetri menengah.
2. Sumbu Simetri
Sumbu simetri pada kristal adalah garis bayangan yang dibuat melewati/menembus pusat kristal, dan bila kristal diputar dengan poros sumbu tersebut sejauh satu putaran penuh akan didapatkan beberapa kali kenampakan yang sama. Sumbu simetri
3. Pusat Simetri
Kristalografi Sistem Kristal
Kristalografi sistem kristal dapat dibedakan menjadi 7, yaitu sistem isometrik, sistem tetragonal, sistem hexagonal, sistem trigonal, sistem orthorhombik, sistem monoklin, dan sistem triklin
1. Sistem Isometrik
Sistem ini juga disebut sistem kristal regular, atau dikenal pula dengan sistem kristal kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristalnya ada 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Dengan perbandingan panjang yang sama untuk masing-masing sumbunya.
Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal Isometrik memiliki axial ratio (perbandingan sumbu a = b = c, yang artinya panjang sumbu a sama dengan sumbu b dan sama dengan sumbu c. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β = γ = 90˚. Hal ini berarti, pada sistem ini, semua sudut kristalnya ( α , β dan γ ) tegak lurus satu sama lain (90˚).
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, sistem Isometrik memiliki perbandingan sumbu a : b : c = 1 : 3 : 3. Artinya, pada sumbu a ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu b ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu c juga ditarik garis dengan nilai 3 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 30˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 30˚ terhadap sumbu bˉ.
Sistem isometrik dibagi menjadi 5 Kelas, yaitu
- Tetaoidal
- Gyroida
- Diploida
- Hextetrahedral
- Hexoctahedral
Beberapa contoh mineral dengan system kristal Isometrik ini adalah gold, pyrite, galena, halite, Fluorite (Pellant, chris: 1992)
2. Sistem Tetragonal
Sama dengan system Isometrik, sistem kristal ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu a dan b mempunyai satuan panjang sama. Sedangkan sumbu c berlainan, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Tapi pada umumnya lebih panjang.
Pada kondisi sebenarnya, Tetragonal memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a = b ≠ c , yang artinya panjang sumbu a sama dengan sumbu b tapi tidak sama dengan sumbu c. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β = γ = 90˚. Hal ini berarti, pada sistem ini, semua sudut kristalografinya ( α , β dan γ ) tegak lurus satu sama lain (90˚).
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, sistem kristal Tetragonal memiliki perbandingan sumbu a : b : c = 1 : 3 : 6. Artinya, pada sumbu a ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu b ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu c ditarik garis dengan nilai 6 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 30˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 30˚ terhadap sumbu bˉ.
Sistem tetragonal dibagi menjadi 7 kelas:
- Piramid
- Bipiramid
- Bisfenoid
- Trapezohedral
- Ditetragonal Piramid
- Skalenohedral
- Ditetragonal Bipiramid
Beberapa contoh mineral dengan sistem kristal Tetragonal ini adalah rutil, autunite, pyrolusite, Leucite, scapolite (Pellant, Chris: 1992)
3. Sistem Hexagonal
Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, dimana sumbu c tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Sumbu a, b, dan d masing-masing membentuk sudut 120˚ terhadap satu sama lain. Sambu a, b, dan d memiliki panjang sama. Sedangkan panjang c berbeda, dapat lebih panjang atau lebih pendek (umumnya lebih panjang).
Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal Hexagonal memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a = b = d ≠ c , yang artinya panjang sumbu a sama dengan sumbu b dan sama dengan sumbu d, tapi tidak sama dengan sumbu c. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β = 90˚ ; γ = 120˚. Hal ini berarti, pada sistem ini, sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120˚ terhadap sumbu γ.
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, sistem Hexagonal memiliki perbandingan sumbu a : b : c = 1 : 3 : 6. Artinya, pada sumbu a ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu b ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu c ditarik garis dengan nilai 6 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 20˚ ; dˉ^b+= 40˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 20˚ terhadap sumbu bˉ dan sumbu dˉ membentuk sudut 40˚ terhadap sumbu b+.
Sistem ini dibagi menjadi 7:
- Hexagonal Piramid
- Hexagonal Bipramid
- Dihexagonal Piramid
- Dihexagonal Bipiramid
- Trigonal Bipiramid
- Ditrigonal Bipiramid
- Hexagonal Trapezohedral
Beberapa contoh mineral dengan sistem kristal Hexagonal ini adalah quartz, corundum, hematite, calcite, dolomite, apatite. (Mondadori, Arlondo. 1977)
4. Sistem Trigonal
Jika kita membaca beberapa referensi luar, sistem ini mempunyai nama lain yaitu Rhombohedral, selain itu beberapa ahli memasukkan sistem ini kedalam sistem kristal Hexagonal. Demikian pula cara penggambarannya juga sama. Perbedaannya, bila pada sistem Trigonal setelah terbentuk bidang dasar, yang terbentuk segienam, kemudian dibentuk segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut yang melewati satu titik sudutnya.
Pada kondisi sebenarnya, Trigonal memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a = b = d ≠ c , yang artinya panjang sumbu a sama dengan sumbu b dan sama dengan sumbu d, tapi tidak sama dengan sumbu c. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β = 90˚ ; γ = 120˚. Hal ini berarti, pada sistem ini, sudut α dan β saling tegak lurus dan membentuk sudut 120˚ terhadap sumbu γ.
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, sistem kristal Trigonal memiliki perbandingan sumbu a : b : c = 1 : 3 : 6. Artinya, pada sumbu a ditarik garis dengan nilai 1, pada sumbu b ditarik garis dengan nilai 3, dan sumbu c ditarik garis dengan nilai 6 (nilai bukan patokan, hanya perbandingan). Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 20˚ ; dˉ^b+= 40˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 20˚ terhadap sumbu bˉ dan sumbu dˉ membentuk sudut 40˚ terhadap sumbu b+.
Sistem ini dibagi menjadi 5 kelas:
- Trigonal piramid
- Trigonal Trapezohedral
- Ditrigonal Piramid
- Ditrigonal Skalenohedral
- Rombohedral
Beberapa contoh mineral dengan sistem kristal Trigonal ini adalah tourmaline dan cinabar (Mondadori, Arlondo. 1977)
5. Sistem Orthorhombik
Sistem ini disebut juga sistem Rhombis dan mempunyai 3 sumbu simetri kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang berbeda.
Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal Orthorhombik memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a ≠ b ≠ c , yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β = γ = 90˚. Hal ini berarti, pada sistem ini, ketiga sudutnya saling tegak lurus (90˚).
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, sistem Orthorhombik memiliki perbandingan sumbu a : b : c = sembarang. Artinya tidak ada patokan yang akan menjadi ukuran panjang pada sumbu-sumbunya pada sistem ini. Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 30˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 30˚ terhadap sumbu bˉ.
Sistem ini dibagi menjadi 3 kelas:
- Bisfenoid
- Piramid
- Bipiramid
Beberapa contoh mineral denga sistem kristal Orthorhombik ini adalah stibnite, chrysoberyl, aragonite dan witherite (Pellant, chris. 1992)
6. Sistem Monoklin
Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari tiga sumbu yang dimilikinya. Sumbu a tegak lurus terhadap sumbu n; n tegak lurus terhadap sumbu c, tetapi sumbu c tidak tegak lurus terhadap sumbu a. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama, umumnya sumbu c yang paling panjang dan sumbu b paling pendek.
Pada kondisi sebenarnya, sistem Monoklin memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a ≠ b ≠ c , yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β = 90˚ ≠ γ. Hal ini berarti, pada ancer ini, sudut α dan β saling tegak lurus (90˚), sedangkan γ tidak tegak lurus (miring).
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, sistem kristal Monoklin memiliki perbandingan sumbu a : b : c = sembarang. Artinya tidak ada patokan yang akan menjadi ukuran panjang pada sumbu-sumbunya pada sistem ini. Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 30˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 45˚ terhadap sumbu bˉ.
Sistem Monoklin dibagi menjadi 3 kelas:
- Sfenoid
- Doma
- Prisma
Beberapa contoh mineral dengan ancer kristal Monoklin ini adalah azurite, malachite, colemanite, gypsum, dan epidot (Pellant, chris. 1992)
7. Sistem Triklin
Sistem ini mempunyai 3 sumbu simetri yang satu dengan yang lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang masing-masing sumbu tidak sama.
Pada kondisi sebenarnya, sistem kristal Triklin memiliki axial ratio (perbandingan sumbu) a ≠ b ≠ c , yang artinya panjang sumbu-sumbunya tidak ada yang sama panjang atau berbeda satu sama lain. Dan juga memiliki sudut kristalografi α = β ≠ γ ≠ 90˚. Hal ini berarti, pada system ini, sudut α, β dan γ tidak saling tegak lurus satu dengan yang lainnya.
Pada penggambaran dengan menggunakan proyeksi orthogonal, Triklin memiliki perbandingan sumbu a : b : c = sembarang. Artinya tidak ada patokan yang akan menjadi ukuran panjang pada sumbu-sumbunya pada sistem ini. Dan sudut antar sumbunya a+^bˉ = 45˚ ; bˉ^c+= 80˚. Hal ini menjelaskan bahwa antara sumbu a+ memiliki nilai 45˚ terhadap sumbu bˉ dan bˉ membentuk sudut 80˚ terhadap c+.
Sistem ini dibagi menjadi 2 kelas:
- Pedial
- Pinakoidal
Beberapa contoh mineral dengan ancer kristal Triklin ini adalah albite, anorthite, labradorite, kaolinite, microcline dan anortoclase (Pellant, chris. 1992)